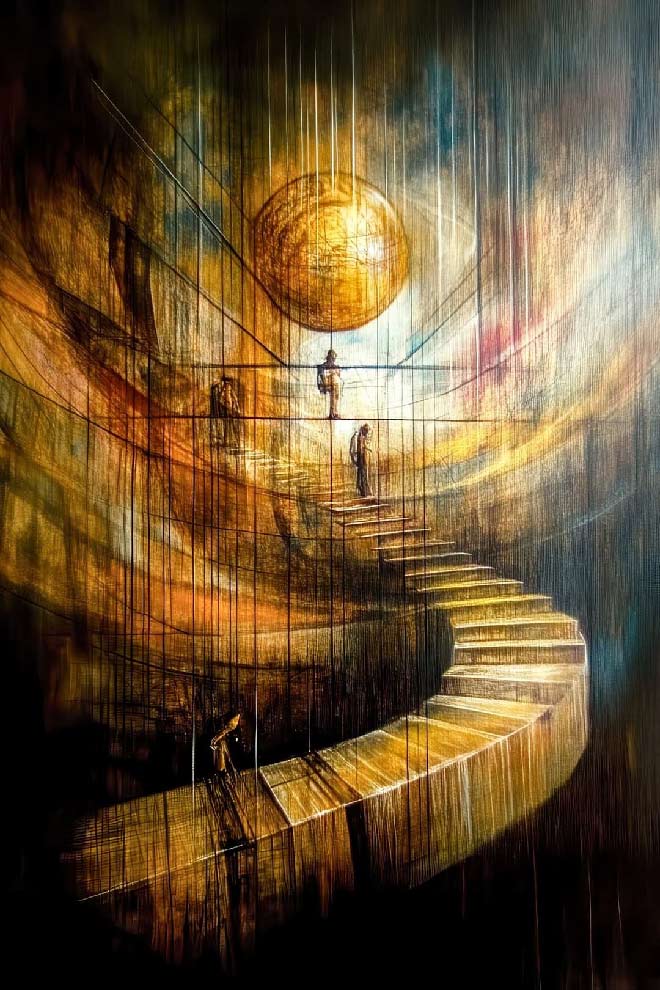Karst Tropis, Epistemologi yang Terabaikan
Di banyak buku teks geologi klasik, karst sering digambarkan sebagai bentang alam berbukit kerucut di Eropa Tengah, dengan gua-gua batu kapur yang kering dan udara dingin yang membeku. Model itulah yang sejak lama mendominasi imajinasi akademik: karst adalah Eropa, gua adalah lorong batu berlapis stalaktit di pegunungan Alpen. Padahal, karst di daerah tropis menyimpan wajah yang sama sekali berbeda. Curah hujan tinggi, vegetasi rimbun, interaksi manusia yang intens, serta dinamika iklim yang lembap membuat karst tropis berkembang dengan logika yang tidak bisa disamakan dengan karst iklim sedang. Seperti kata Ford dan Williams (2007), “karst tropis memiliki kompleksitas yang jauh melampaui kerangka analisis yang dibangun dari pengalaman Eropa.”
Gunung Sewu di Jawa atau kawasan Bantimurung-Bulusaraung di Sulawesi adalah contohnya. Bukit-bukit kapur di sana tidak hanya berdiri sebagai kerucut batu yang sunyi, melainkan bagian dari mosaik kehidupan: lembah dolina yang menjadi sawah, gua yang berfungsi sebagai tempat tinggal, hingga mata air yang menghidupi desa. Hujan deras di daerah tropis mempercepat pelarutan batuan, membentuk jaringan sungai bawah tanah yang rumit dengan debit yang sulit diprediksi. Metode hidrogeologi klasik sering kali gagal menangkap kerumitan semacam ini, sehingga peta aliran air tidak jarang keliru, sementara masyarakat tetap bergantung pada naluri dan pengalaman panjang untuk membaca lanskap karst.
Inilah epistemologi yang terabaikan: cara memahami karst yang tidak berhenti pada batu dan air, tetapi juga merangkul kehidupan manusia. Karst tropis adalah ekosistem sosial sekaligus hidrologis. Ia adalah laboratorium terbuka tempat iklim, geologi, dan budaya saling membentuk. Namun dalam banyak kurikulum geologi dan geografi di Indonesia, kita masih terikat pada narasi Eropa. Nama Slovenia atau Austria lebih akrab di telinga mahasiswa daripada Maros, Pacitan, atau Sangkulirang, padahal di situlah letak pengalaman empiris yang seharusnya menjadi dasar pengetahuan kita.
Kelemahan epistemologis ini bukan persoalan akademik semata. Dampaknya terasa nyata, terutama dalam pengelolaan air. Di karst tropis, sumber daya air tersimpan di lorong bawah tanah yang tersembunyi. Jika dianalisis dengan kerangka klasik, kapasitas penyimpanan sering salah diperkirakan, ketersediaan air disalahpahami, bahkan strategi konservasi pun salah arah. Akibatnya, desa-desa karst yang sesungguhnya memiliki potensi cadangan air tetap menghadapi krisis setiap musim kemarau, karena teknologi dan kebijakan tidak memahami anatomi karst tropis.
Eksploitasi batu kapur untuk industri semen pun sering bertumpu pada pandangan bahwa karst hanyalah tumpukan komoditas pasif. Padahal, di daerah tropis, bukit kapur berfungsi ganda: sebagai reservoir air, penopang ekologi, dan ruang budaya. Kesalahan perspektif inilah yang membuat setiap penambangan kerap dipandang hanya dari sisi ekonomi, sementara konsekuensi sosial dan ekologisnya terlupakan.
Lebih jauh, karst tropis juga menyimpan dimensi kultural. Gua-gua di Indonesia bukan sekadar rongga batu, melainkan arsip kehidupan: lukisan berusia puluhan ribu tahun, fosil fauna purba, hingga jejak awal manusia Nusantara. Namun karena lensa yang digunakan masih Eropa-sentris, penafsiran gua sering berhenti pada catatan geologi, sementara makna budaya hanya disinggung sekilas. Padahal di sanalah kekhasan karst tropis: ia merekam kehidupan alam dan manusia dalam satu ruang.
Membangun ilmu karst tropis berarti menulis ulang kerangka berpikir. Kita memerlukan metodologi baru: hidrogeologi yang mampu membaca variabilitas tropis, arkeologi yang berpadu dengan geomorfologi, antropologi yang mengindahkan suara masyarakat. Indonesia, dengan kawasan karst lebih dari 15 juta hektar, seharusnya tidak lagi menjadi objek studi belaka, tetapi pusat penghasil pengetahuan. Dari sini, dunia bisa belajar bahwa karst tropis memiliki epistemologi berbeda, sama sahihnya dengan karst Eropa.
Pada akhirnya, membicarakan karst tropis berarti menegaskan martabat pengetahuan kita. Selama kita masih meminjam lensa Eropa, kita akan terus salah membaca bentang alam sendiri. Tetapi ketika kita berani merumuskan epistemologi karst tropis, Indonesia dapat tampil sebagai pelopor: menulis bab baru geosains dunia dari bukit-bukit yang hijau, basah, dan penuh kehidupan.
Daftar Pustaka
- Bogaerts, M., & Waltham, T. (2009). Karst and Caves: A Geological Adventure. London: Springer.
- Ford, D. C., & Williams, P. (2007). Karst Hydrogeology and Geomorphology. Wiley.
- Day, M. J., & Urich, P. B. (2000). An Assessment of Protected Karst Landscapes in Southeast Asia. Cave and Karst Science, 27(2), 61–70.
- Gillieson, D. (1996). Caves: Processes, Development, and Management. Oxford: Blackwell.
- Kusumayudha, S. B. (2010). Karst Indonesia: Bentang Alam, Air Tanah, dan Pengelolaannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Palmer, A. N. (2007). Cave Geology. Dayton, OH: Cave Books.
- Vermeulen, J. J., & Whitten, A. J. (1999). Biodiversity and Cultural Heritage in Karst. Jakarta: Ford Foundation.
- Waltham, T., Bell, F., & Culshaw, M. (2005). Sinkholes and Subsidence: Karst and Cavernous Rocks in Engineering and Construction. Chichester: Springer.