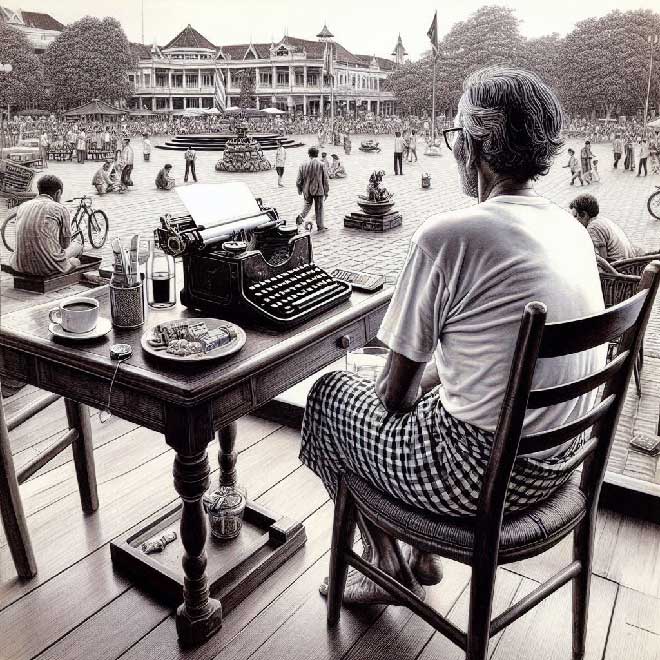Ketika 'Sopan Santun' Menjadi Algoritma Penjinakan Manusia
Di sebuah kafe di jantung kota, seorang wanita muda menatap gelas
kopinya yang sudah dingin. Di meja sebelah, dua lelaki berjas rapi
tertawa lepas sambil membicarakan rencana mem-PHK ratusan karyawan demi
"efisiensi perusahaan". Pelayan mendekat, tersenyum manis, menawarkan
menu penutup. Mereka mengangguk sopan, memesan kue cokelat mahal—seolah
kehangatan senyum pelayan bisa menebus dinginnya keputusan yang akan
mereka ambil. Di sudut lain, seorang ibu tua membungkuk memungut sampah
yang diinjak seorang eksekutif muda. Ia mengucapkan "maaf" sambil
menyerahkan botol plastik ke tukang kebersihan, meski tak ada yang salah
padanya. Di ruang ini, sopan santun bertepuk tangan sambil menari di
atas panggung ketidakadilan.
Inilah paradoks peradaban: kita hidup
dalam tarian rumit antara bisikan hati, pertarungan akal, dan tuntutan
sosial. Seperti tiga dewa yang saling bersaing, moral, etika, dan etiket
mengatur langkah manusia—seringkali tak selaras, kadang bertabrakan. Di
negeri ini, di mana "sopan-santun" kerap dijadikan tameng untuk
membungkam kritik, atau "tradisi" dipakai untuk mengukuhkan hierarki,
kita lupa bahwa ketiga konsep ini bukan sekadar teori. Mereka adalah
darah yang mengalir dalam nadi interaksi manusia, kadang menyembuhkan,
kadang meracuni.
Bisikan Hati di Tengah Gemuruh Kepentingan
Moral
adalah suara pertama yang lahir dari kegelapan batin. Ia muncul tanpa
undangan—seperti rasa sesak saat melihat seorang anak dihukum karena
mencuri roti, atau getar marah ketika tetangga memaki pekerja migran. Di
sebuah desa di Jawa Timur, Pak Kardi—guru honorer berusia 58
tahun—memilih meminjamkan separuh gajinya yang tak seberapa untuk biaya
sekolah anak-anak miskin. "Hati saya tak bisa diam kalau melihat mereka
putus sekolah," katanya, sambil menatap sepatu bututnya. Ini moral dalam
bentuknya yang paling jujur: tak butuh teori filsafat, tak perlu
seminar etika. Ia adalah denyut nurani yang mengatakan, "Ini salah,"
atau "Ini benar," tanpa peduli pada konsekuensi sosial.
Tapi dunia
tak selalu ramah pada bisikan hati. Di kantor-kantor megah, para
eksekutif belajar mematikan suara ini. Mereka menyebutnya
"profesionalisme"—padahal seringkali itu hanyalah topeng untuk
membenarkan keputusan yang melukai ribuan orang. Seperti karakter
Raskolnikov dalam Crime and Punishment, mereka mencoba
meyakinkan diri bahwa "tujuan mulia" membenarkan cara-cara keji. Tapi
Dostoevsky mengingatkan: dosa sejati bukanlah pelanggaran hukum,
melainkan pengkhianatan terhadap bisikan batin. Di Indonesia, kita
menyaksikan ironi ini setiap hari: koruptor yang tersenyum di
persidangan, sementara pencuri ayam dipenjara lima tahun. Hukum mungkin
bisu, tapi seperti kata novelis Rusia itu, "Jiwa tak pernah lupa."
Etika: Jembatan antara Hati dan Akal
Jika
moral adalah api yang membara, etika adalah panduan agar api itu tak
membakar habis segalanya. Di sini, akal bicara. Etika tak puas dengan
jawaban, "Ini benar karena hati saya mengatakan demikian." Ia menuntut
pertanggungjawaban: "Mengapa ini benar? Apa konsekuensinya? Siapa yang
dirugikan?" Di ruang kuliah suatu universitas ternama, seorang dosen
filsafat memprovokasi mahasiswanya: "Jika kau harus memilih antara
menyelamatkan satu orang yang kau cintai atau lima orang asing, apa yang
kau lakukan?" Diskusi pun memanas. Ada yang mengutip Kant tentang
imperatif kategoris, ada yang merujuk utilitarianisme. Tapi di sudut
ruangan, seorang mahasiswa berkaca-kaca: "Saya tak mau memilih. Saya
ingin menyelamatkan semuanya."
Etika, dalam denyutnya yang paling
hidup, adalah upaya manusia untuk tetap manusiawi di tengah dilema. Di
negeri ini, di mana UU kerap dijadikan alat untuk melegalkan
ketidakadilan, etika menjadi senjata perlawanan. Ketika sebuah
perusahaan tambang mengklaim telah "beretika" karena memberi CSR sambil
meracuni sungai, etika menampar mereka dengan pertanyaan: "Apa gunanya
membangun sekolah jika anak-anak tak bisa minum air bersih?" Voltaire,
melalui Zadig, mengajarkan bahwa kebaikan sejati adalah
keberanian melawan absurditas—meski harus melanggar "tata krama". Di
sini, etika bukanlah buku pedoman, melainkan pisau bedah yang membedah
kepalsuan di balik jargon-jargon "kepatuhan".
Etiket: Topeng yang Kadang Menjadi Penjara
Etiket
adalah bahasa yang paling lihai—ia bisa menjadi pelumas sosial, tapi
juga jerat yang membelenggu. Di Jepang, seorang karyawan harus
membungkuk 45 derajat saat menyapa atasan. Di Bali, senyum ramah adalah
keharusan, bahkan saat hati sedang terluka. Di kantor pemerintahan
Jakarta, staf junior diajari untuk "tidak boleh lebih pintar dari
atasan" dalam rapat. Semua ini adalah etiket: aturan tak tertulis yang
menjaga mesin sosial tetap berjalan.
Tapi seperti kata Oscar
Wilde, "Sopan santun adalah seni membuat musuh merasa nyaman sebelum kau
menghancurkannya." Di sebuah pesta pernikahan mewah, para tamu
bersalaman hangat sambil membisikkan gosip tentang mempelai. Di ruang
rapat direksi, para eksekutif tersenyum sopan sambil merancang strategi
memangkas hak pekerja. Etiket, dalam sisi gelapnya, adalah seni
berpura-pura—alat untuk menyembunyikan kejahatan dalam bingkai
kesantunan. Di Indonesia, kita mahir dalam permainan ini: menyebut
korupsi sebagai "uang rokok", atau kekerasan aparat sebagai "pembinaan".
Namun
etiket juga punya kekuatan magis. Di pelosok Flores, seorang nenek
menawarkan sirih pinang pada tamu—ritual yang bukan sekadar sopan
santun, melainkan cara menjaga martabat manusia. Di sini, etiket bukan
topeng, melainkan jembatan antargenerasi. Persoalannya, seperti
diingatkan Nietzsche, adalah ketika kita menganggap etiket sebagai
pengganti moral. "Masyarakat yang menjadikan kesopanan sebagai agama,"
tulisnya, "akan mati perlahan karena kebohongan yang
diinstitusionalkan."
Tarian yang Tak Pernah Selesai
Lantas,
bagaimana menari di antara ketiganya? Seorang aktivis lingkungan di
Kalimantan memberi contoh nyata. Saat perusahaan sawit menawarinya "uang
damai", ia menolak dengan sopan: "Terima kasih, tapi saya lebih baik
makan nasi dengan garam daripada menjual hutan." Di sini, moral menolak,
etika memberikan alasan ("hutan adalah nafas masyarakat adat"), dan
etiket menjaga agar penolakan tak menjadi konflik terbuka.
Tapi
tarian ini tak selalu elegan. Di suatu malam di Yogyakarta, sekelompok
mahasiswa memilih protes keras saat kampus menaikkan uang kuliah. Mereka
dianggap "tidak sopan", tapi seperti kata pemimpin aksi itu, "Kadang,
melanggar etiket adalah harga yang harus dibayar agar suara kami
didengar." Di sini, etika dan moral bersekutu melawan etiket yang
membungkam.
Sejarah manusia adalah sejarah pertarungan ketiganya.
Budha Gautama meninggalkan kemewahan istana (melawan etiket kerajaan)
untuk mencari kebenaran (moral). Sokrates meminum racun demi
mempertahankan prinsip (etika), meski pengadilan Athena menganggapnya
"tak sopan". Di Indonesia modern, kita melihat guru-guru seperti Butet
Manurung yang "melanggar etiket" dengan mengajar anak Suku Anak Dalam
tanpa izin birokrasi—tindakan yang dianggap "baik" oleh moral, "benar"
oleh etika, tapi "tak sopan" oleh sistem.
Luka yang Harus Tetap Terbuka
Di
terminal bus tua ibu kota, seorang pengamen tunanetra menyanyikan lagu
tentang keadilan. Para penumpang sibuk dengan ponsel, tak ada yang
memberinya koin. Seorang anak kecil tiba-tiba berdiri, mengacungkan
jempol, dan berteriak, "Suaramu bagus, Om!" Sang pengamen
tersenyum—sebuah momen kecil di mana moral (kepolosan anak), etika
(apresiasi pada seni), dan etiket (pujian spontan) menyatu tanpa
konflik.
Tapi dunia bukan terminal bus. Di sini, ketiganya lebih
sering berbenturan daripada berdamai. Mungkin itu baik adanya—karena
selama konflik ini ada, manusia masih punya hasrat untuk menjadi lebih
baik. Seperti kata Rumi, "Cahaya masuk melalui celah-celah yang
retak." Retakan antara moral, etika, dan etiket itulah yang memungkinkan
kita tetap manusia: kadang kaku dalam kesopanan, kadang berani dalam
kebenaran, tapi sering—bahkan mungkin selalu—berjuang untuk tidak sepenuhnya tunduk
pada topeng-topeng yang kita buat sendiri.
Di ujung hari, ketika lampu kota mulai menyala dan topeng-topeng sosial kembali dikenakan, bisikan hati tetap terdengar: "Apakah kita sudah cukup baik—bukan sekadar sopan, bukan hanya benar—tapi manusiawi?"
Pertanyaan ini, yang tak akan pernah ada jawaban finalnya, adalah
hadiah sekaligus kutukan terbesar peradaban. Dan dalam hening diam, ia
adalah alasan mengapa kita masih pantas disebut manusia.